
Judul : The Righteous Mind, Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama
Penulis : Jonathan Haidt
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Tahun : 2020
Tebal : xv + 464 halaman
Rangkaian Pemilu 2024 telah usai. Rasa-rasanya sebagian besar orang merasakan betapa nuansa polarisasi dan keterpecahan merebak di tengah masyarakat. Masyarakat terbelah menjadi pendukung calon presiden si ini dan si itu. Dan rasa-rasanya pula suasana yang nampak kisruh tersebut masih terus berlangsung hingga kini jika kita melihat di televisi para elit masih berdebat tentang proses Pemilu yang telah berlalu.
Saling serang antar pendukung paslon di dunia maya menjadi rutin setiap saat. Saling lempar tuduhan dan saling menyematkan stigma buruk kepada pendukung berbeda membuat suasana kian keruh. Seakan-akan argumentasi tidaklah penting, yang utama adalah intuisi: tidaklah penting alasanmu, yang terpenting adalah calon presidenku yang terbaik.
Perang psikologis bernuansa moral lebih kuat daripada saling tanding gagasan. Mengapa bisa demikian? Mengapa kita terpecah karena politik—dan dalam kasus lain juga terpecah karena agama? Mengapa orang-orang tidak peduli pada rasionalitas, dan kecenderungannya malah rasionalitas yang mengikuti kepentingan moral kita sebagai pendukung calon tertentu? Rasionalitas justru dijadikan ‘pembenaran’ untuk memposisikan diri kita sebagai yang paling benar?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dielaborasi dan ditelisik jawabannya oleh Jonathan Haidth, ahli psikologi asal Amerika Serikat, dalam bukunya, “The Righteous Mind, Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama.” Menawarkan sudut pandang baru dalam psikologi moral, kesimpulan Haidt dapat membawa kita pada solusi alternatif untuk kita kembali merekat hubungan kemanusiaan yang sempat terputus oleh kontestasi politik maupun identitas keagamaan.
Buku Haidt yang relatif tebal ini—mendekati 500an halaman dengan dimensi buku sedikit lebar—terbagi ke dalam tiga bagian (di luar kata pengantar). Bagian pertama berjudul, “Intuisi Duluan, Penalaran Strategis Belakangan.” Pada bagian permulaan ini, Haidt membawa kita pada sumber atau akar munculnya moralitas. Di bagian ini ada semacam perumpamaan menarik dan berkali-kali hadir dalam penjelasan sepanjang buku, yakni hubungan gajah dan penunggangnya yang mengumpamakan hubungan intuisi dan penalaran.
Bagian kedua bertajuk, “Moralitas Lebih Daripada Sekadar Bahaya dan Ketidakcurangan”. Dengan menganalisa fenomena psikologi moral yang fokus pada masyarakat Amerika Serikat, Haidt menghamparkan bukti-bukti dan kesimpulan-kesimpulan menarik dan detail terkait pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana orang-orang di kelompok tertentu mempertahankan intuisinya dibanding nalarnya. Kata Haidt, setiap orang memiliki fondasi moral berbeda. Di sini kita akan berkenalan dengan enam fondasi: harm (bahaya), justice (keadilan/ketidakcurangan), sanctity (kesucian), loyalty (kesetiaan), dan liberty (kebebasan).
Dan bagian ketiga, “Moralitas Mengikat dan Membutakan”. Di bagian terakhir ini Haidt membawa kita pada penjelasan seputar hal-hal seperti mengapa kita suka berkelompok, bagaimana psikologi moral berperan dalam orang-orang beragama, dan sebagainya. Di sini Haidt meminjam hasil-hasil penelitian dalam evolusi dan biologi, seperti teori Darwin tentang seleksi kelompok.
Salah satu kesimpulan paling kuat dari seluruh udaran Haidt dalam buku ini adalah bahwa kita dalam memilih pemimpin atau mempertahankan kelompok pertama-tama dituntun oleh intuisi, bukan nalar. Haidt menganalogikan hal ini dengan gajah dan penunggangnya. Pemaparan tentang ini sebetulnya cukup rinci dihamparkan oleh Haidt agar kita tidak menyederhakan hubungan antara penilaian moral dengan akal kita. Namun, kita bisa sederhakan bahwa gajah adalah intuisi kita atau penilaian moral kita. Sementara itu, sang penunggang adalah akal yang sesungguhnya mengikuti ke mana gajah pergi.
Hubungan gajah dan penunggang memang tidaklah sederhana, di satu sisi gajah memanglah membawa si penunggang, tapi di sisi lain gajah tersebut juga tergantung pada arahan-arahan si penunggang. Di pihak si penunggang juga tidak sederhana: dia memang dapat melihat sesuatu di kejauhan sehingga pikirannya jernih, dia juga dapat mempelajari teknik-teknik baru dalam mengarahkan si gajah.
Namun, mengapa Haidt menggunakan analogi gajah alih-alih kuda? Karena, kata Haidt, gajah jauh lebih besar dan lebih cerdas daripada kuda.
Jika kita telah jernih menangkap seluruh penjelasan Haidt, kita akan dapat menyusun kerangka solusi alternatif agar bagaimana kondisi kterpecahan dan keterbelahan itu dapat direkatkan. Karena kesimpulan Haitd mengatakan bahwa intuisi selalu mendahului penilaian kita secara moral sebelum nalar, maka jawaban solutifnya adalah bukan dengan pendekatan nalar, namun sesuatu yang intuitif pula: kita tak bisa mengubah pendirian kubu atau kelompok tertentu hanya dengan alasan logis dan agumentasi rasional, namun kita bisa menyentuh sisi intuisinya. Empati, barangkali?
Kita diberitahu oleh Haidt orang yang berbeda dengan kita tetaplah orang-orang baik. Hanya saja kita orang-orang baik yang terpecah karena politik dan agama. Kita harus menggerakkan sang gajah alih-alih mengubah pendirian si penunggang.

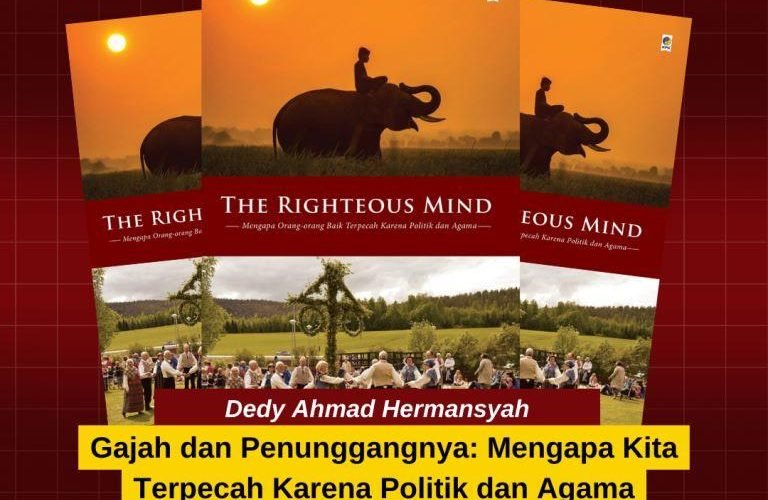






1 Komentar