
Judul : Di Ampenan, Apa Lagi yang Kau Cari?
Penulis : Kiki Sulistyo
Penerbit : BASABASI
Cetakan : pertama, Mei 2017
Halaman : 92 hlm
Memang benar apa yang dikatakan Afrizal Malna dalam epilog buku kumpulan puisi ini, kumpulan puisi Kiki Sulistyo, “Di Ampenan, Apa Lagi yang Kau Cari?” bisa dilihat sebagai balada panjang tentang Ampenan. Dan saya memang tergoda membacanya seperti itu.
Balada Ampenan yang dihadirkan Kiki dalam buku puisinya yang meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa 2017 itu dijejali oleh kisah keluarga, sejarah kota, dan kenangan yang melulu pilu. Meski Kiki dalam kata pengantarnya mengatakan tak hendak menjadi sejarawan atau berkisah dengan meminjam mata orang lain dalam menceritakan perihal Ampenan dengan segala peristiwa yang meliputinya, namun saya didorong masuk ke dalam batin sejarah kotanya. Meski nampak personal dan sentimental—sebagaimana diakui sendiri oleh penyairnya—konflik dan masalah-masalah keluarga dapat juga dilihat sebagai cerminan masalah sosial.
Pendeknya: buku puisi ini adalah dokumentasi sejarah sosial dari sudut pandang subyektif.
Balada panjang perihal Ampenan ini disusun layaknya bab-bab dalam roman yang memiliki alur, konflik, dan penutup. Dilihat dari susunan daftar isinya, saya melihat seperti ini: bagian pertama, Kiki seperti hendak memperkenalkan kita pada situs atau lanskap penting di masa lalunya. Ini nampak dari judul-judulnya yang menyebut tempat: simpang lima; pantai ampenan; kampung nelayan, pondok perasi; kubur dende; bioskop Ramayana; sekolah dasar nomor lima abah husein; dan kawasan makelar.
Pada bagian kedua, Kiki kemudian mengajak kita berkenalan dengan orang-orang atau tokoh dalam masa lalunya. Ini terlihat dari judul-judulnya yang menyebut nama orang: itje, paman, siau lim, ida, bibi keriting, paman bun, papuq kebon, dll.
Bagian ketiga, kita mulai diajak masuk ke dalam belukar peristiwa yang terjalin dengan situs atau lanskap dan orang-orang tadi. Nostalgia akan cinta terlarang, potret muram keluarga, tentang paman dan (hantu) ladang, tentang perebutan harta warisan.
Bagian keempat, bagian terakhir, adalah bagian sedikit reflektif perihal Ampenan, harapan akan Ampenan, dan apa-apa yang telah hilang dari Ampenan. Sebagian dikisahkan dalam momen kepulangan, sebagian lagi dalam momen penantian.
Maka dengan demikian, Ampenan dalam puisi Kiki hadir kadang sebagai personifikasi, kadang juga sebagai puing-puing ingatan dan kenangan, yang melulu pilu, melulu haru. Ampenan hadir sebagai “siau lim”: “siau lim seperti kota ini/pucat dan kesepian.”(siau lim, hlm 26). Atau hadir sebagai seseorang yang disebut ‘kau’: “kota ini bagai kau yang berpalang ingatan/ ajarkan aku memasukinya dengan tenang.” (ajarkan aku bagaimana memasuki sebuah kota, hlm 53).
Ketika hadir sebagai puing-puing, Ampenan benar-benar hanya berupa kenangan dan ingatan: “…kenangan, satu-satunya yang tersisa dari Ampenan.” (pulang ke ampenan, hlm 45). Atau Ampenan adalah “kota ini tak menyisakan apa-apa/kecuali kanvas kelabu, kelabu tua.” (angin berjalan dari selatan, hlm 57). Untuk itu semua, Ampenan menjadi “kota yang kian jalang/ melupakan semua yang ingin ku kenang.” ( ampenan, ke mana aku akan menjelang, hlm 58).
Kesan-kesan Ampenan yang muram dan murung itu berjalin-kelindan dengan kisah-kisah manusia dan perubahan kota yang secara arsitektural dan sosial kian banyak yang hilang. Berpedoman pada masa lalunya, Kiki tak menemukan lagi (tiang-tiang) pelabuhan, bioskop, dan gedung-gedung telah menjadi tua. Rumah dalam pengertian ruang dan fisik tidak lagi utuh, atau hilang sama sekali.
Ketika mengisahkan tentang kehilangan, Kiki mencoba membahasakannya lewat camar. Kita akan menemukan camar dalam tiga puisinya: pegadaian; laut menatapku; dan angin berjalan dari selatan. Camar dalam tiga puisi ini tidak hadir sebagai pernik belaka, akan tetapi, setidaknya bagi saya, dia dihadirkan untuk menyampaikan pesan tertentu oleh penyairnya.
Dalam “pegadaian”, “seperti ilham dari camar yang tak mendapat tiang, lantas menjauh dari pelabuhan.” Dalam “laut menatapku”, “akan datang sekelompok camar/mencari jejak moyang.” Sekawanan camar dalam puisi ini, seperti pada puisi “pegadaian”, juga tak mendapat tiang untuk persinggahan. Camar-camar ini kemudian bertengkar, berebut tempat. Ini sedikit mirip dengan kisah-kisah sebagian tokohnya dalam keluarganya yang terusir oleh paman sendiri, berebut harta warisan, dan karenanya harus ada yang pergi. Masalah camar ini bertautan juga dengan masalah “pertengkaran para pendatang, warisan yang sudah diruntuhkan”, dalam puisi “lubang malam ampenan” (hlm 56).
Camar juga kita dapat ditemukan dalam “angin berjalan dari selatan”, “dari jauh sepasang camar bertukar kabar.” Dalam puisi ini, camar yang tidak melihat biji-biji di permukaan tanah bersanding dengan kisah keluarga yang memimpikan sebuah rumah.
Begitulah Kiki menghadirkan kisah balada Ampenan yang berisi fragmen sejarah keluarga, lengkap dengan detail-detail tempat dan kenangan yang begitu lekat akannya (bioskop, pelabuhan, ladang, toko-toko, dll). Ditambah pula persentuhannya dengan orang-orang di lingkungannya yang terdiri dari berbagai suku bangsa (Melayu, Tionghoa, Arab) yang memberikan kita gambaran betapa majemuk identitas yang terkandung di dalam kota Ampenan.
Dan, menarik juga istimewanya, itu dibentangkan dalam kumpulan puisi yang disusun dalam susunan isi yang tepat. Nampak sekali hal ini dipersiapkan dengan matang sebelum kemudian disajikan dalam bentuk buku. Kiki mengatakan, puisi-puisi dalam kumpulan ini telah disusun ulang dan ada yang mengalami perubahan judul. Saya juga melihat tidak ada titimangsa tanggal atau tahun di bawah setiap puisi (menurut saya ini memang pilihan yang sangat tepat, agar kita bisa membaca keseluruhan puisi sebagai rangkaian alur yang sambung-menyambung).
Ampenan dalam puisi Kiki tidak hadir sebagai sebentuk kegembiraan, eksotisme, dan puja-puji kejayaan masa lalu sebagai pelabuhan utama tempat bersandar kapal-kapal dari Eropa. Dari puisi pembukanya, VARIASI HIKAYAT AMPENAN, Kiki sudah mendedahkan perihal “…penaklukan/ akan dimulai dari setabir kebohongan..” Kiki membuat versi sendiri tentang risalah nama Ampenan. “Maka ia tancapkan serat ampan ke getir pasir/hanya untuk membuat tanda, nama tua sebuah kota.”
Dan lewat daun ampan itulah Kiki berseru dalam puisi terakhirnya, “daun ampan, daun ampan, tunjukkan padaku/jalan ke Ampenan, tunjukkan padaku/jalan ke lubang masa silam, yang hilang/yang hilang di tengah halimun perubahan.”
Dedy Ahmad Hermansyah. Kelahiran Sumbawa Besar, NTB. Berdomisili di Kota Mataram. Pustakawan di Komunitas Taman Baca, Kota Mataram, NTB.

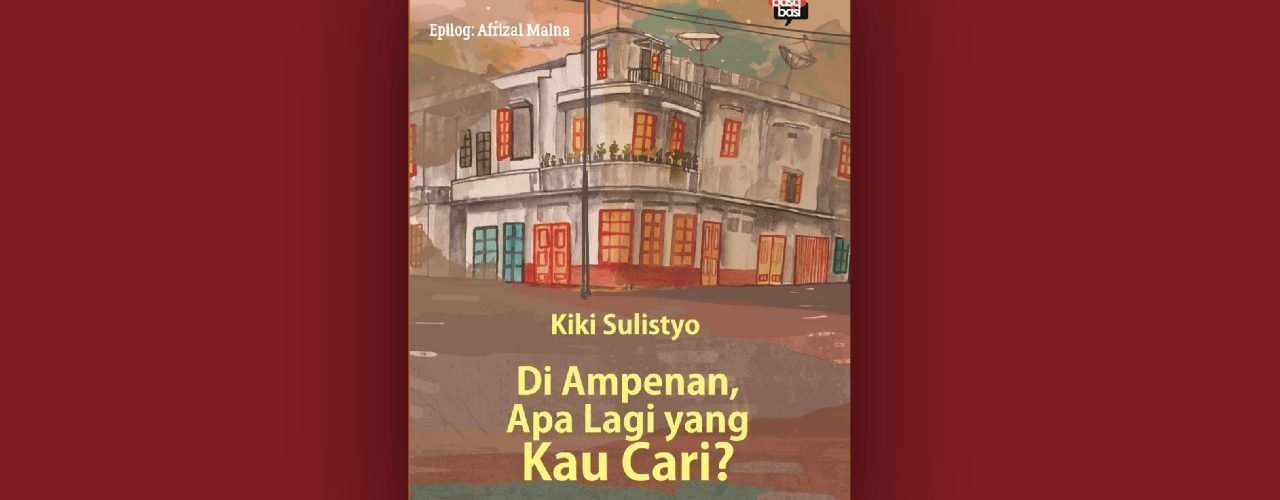






Tambahkan Komentar