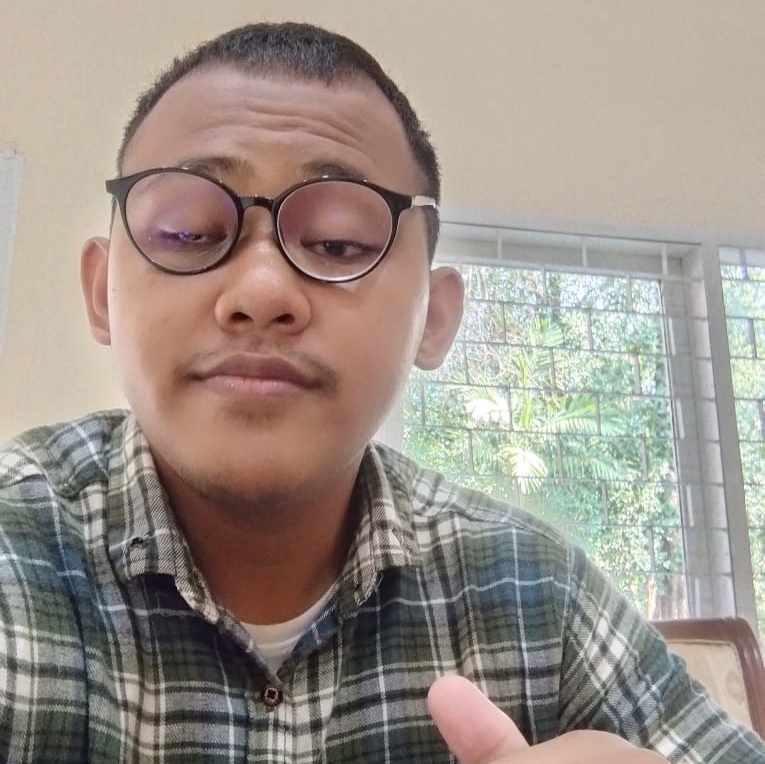
oleh: Ilham ( Mahasiswa Ilmu Komunikasi / Relawan Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin)
Sebelum memulai tulisan ini, saya ingin mengajak anda merenung sejenak. Pernahkah anda melihat difabel berwisata di tempat umum seperti pantai, taman kota, atau destinasi wisata terkenal lainnya? Kalau iya, seberapa sering itu terjadi? Dan ketika kamu melihat mereka, apakah mereka tampak menikmati tempat itu sepenuhnya—atau justru hanya duduk di pinggir, sekadar menonton orang lain bersenang-senang?
Pertanyaan itu mungkin sederhana. Tapi ketika dijawab jujur, kita akan dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia pariwisata kita, sebagus dan seindah apa pun narasi promosinya, belum benar-benar “untuk semua.” Dalam banyak kesempatan, difabel masih belum dianggap sebagai bagian dari kelompok yang berhak menjadi wisatawan. Keberadaan mereka sering kali luput dalam perencanaan, pembangunan, maupun pelayanan destinasi wisata.
Saya teringat masa kecil saya dulu saat keluarga mengajak saya ke Taman Wisata Bantimurung. Saya masih ingat betapa serunya berenang bersama, berseluncur, dan menikmati pemandangan kupu-kupu yang berterbangan. Saat itu, saya hanya seorang anak yang menikmati hari libur tanpa beban. Tapi hari ini, sebagai seorang difabel sensorik penglihatan, saya mulai mempertanyakan ulang pengalaman masa kecil saya—dan apa jadinya kalau dulu saya sudah menjadi difabel seperti sekarang. Masihkah saya bisa bermain dan menikmati semuanya?
Pertanyaan itu tak kunjung hilang dari pikiran saya. Karena pada kenyataannya, aksesibilitas di tempat wisata bukan sekadar soal fisik seperti tangga, jalanan, atau toilet. Ia adalah refleksi dari sebuah sistem sosial yang sering gagal melihat bahwa wisata adalah hak, bukan kemewahan. Bahwa setiap orang—tanpa kecuali—berhak menikmati keindahan alam, sejarah, dan budaya yang ditawarkan pariwisata.
Indonesia, negeri yang dikenal dunia karena kekayaan alamnya—dari Raja Ampat dengan surga bawah lautnya hingga Bali yang menjadi magnet turis dunia—sayangnya belum cukup inklusif dalam menyambut semua wisatawan. Kita bisa membanggakan eksotisme dan kehangatan tropis, tetapi lupa bertanya: apakah tempat-tempat itu benar-benar bisa diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda? Apakah jalan setapak menuju pantai sudah ramah untuk tunanetra? Apakah informasi tersedia dalam berbagai format yang bisa diakses oleh semua?
Inilah yang membuat saya terpanggil untuk menggugat satu pertanyaan penting: wisata itu untuk siapa?
Di Makassar, kota tempat saya tinggal, pernah digagas visi besar “Makassar Kota Dunia.” Sebuah mimpi besar yang seharusnya berarti bahwa kota ini menjadi milik semua orang, dari berbagai latar belakang, termasuk difabel. Tapi kenyataannya, ketika saya berbincang dengan seorang pegiat wisata, ia berkata bahwa banyak destinasi seperti lorong wisata, Anjungan Pantai Losari, atau waterboom masih belum bisa diakses oleh difabel. Bahkan sekadar jalan menuju fasilitas saja belum dirancang inklusif. Difabel hanya bisa menonton, bukan menikmati.
Ironis, bukan? Di satu sisi, kota ini mengklaim diri sebagai kota dunia yang terbuka dan modern. Tapi di sisi lain, ada kelompok yang bahkan tidak bisa masuk ke tempat wisata, apalagi menikmati suasana yang ditawarkan. Mereka hanya menjadi pajangan kota—objek charity yang sesekali dimunculkan untuk kepentingan citra dan pencitraan, tapi tidak sungguh-sungguh dilibatkan sebagai subjek yang punya hak.
Dan bukan hanya akses fisik yang jadi masalah. Ketika difabel hadir di ruang publik, kami masih harus menghadapi stigma. Pertanyaan semacam, “Kok bisa sampai di sini?” atau “Siapa yang dampingi kamu?” sering terdengar, seolah kami tidak punya kemandirian. Padahal kami hadir bukan untuk menantang norma, tetapi untuk menjalankan hak kami—termasuk hak untuk menjadi turis di negeri kami sendiri.
Di sinilah gagasan Tourism For All menjadi sangat relevan. Sebuah konsep yang ingin menegaskan bahwa wisata bukan hanya untuk mereka yang dianggap “normal.” Bahwa seseorang yang tidak bisa melihat dengan kedua mata, yang berjalan dengan kursi roda, atau yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat, juga punya hak untuk menjadi wisatawan. Hak untuk menikmati, tertawa, berlibur, dan menciptakan kenangan indah.
Tourism For All bukan sekadar slogan. Ia adalah panggilan untuk perubahan sistemik. Tempat wisata tidak akan inklusif hanya dengan menambahkan jalur landai atau lift. Kita butuh lebih dari itu: pelibatan aktif difabel dalam perencanaan dan desain wisata, pelatihan bagi petugas layanan publik agar memahami kebutuhan pengunjung difabel, penyediaan informasi dalam format alternatif (seperti braille, audio, dan bahasa isyarat), hingga penyusunan kebijakan yang berpihak pada pariwisata inklusif.
Sudah saatnya pemerintah kota, pelaku pariwisata, akademisi, dan organisasi difabel duduk bersama, membangun panduan dan rekomendasi yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman hidup difabel. Karena siapa lagi yang paling tahu kebutuhan difabel kalau bukan mereka sendiri?
Saya masih ingat betul hari itu. Kami berdiri di bawah terik matahari, memandang laut dari Anjungan Pantai Losari. Bukan sekadar kunjungan biasa. Hari itu, saya bersama tim asesmen inklusivitas dari Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, akademisi, praktisi pariwisata, dinas pariwisata, serta organisasi disabilitas lainnya, menguji aksesibilitas kawasan wisata paling ikonik di Makassar. Bukan hanya sekadar menilai, tapi menantang asumsi lama: bahwa wisata hanya untuk mereka yang dianggap “normal.”
Asesmen ini adalah bagian dari perayaan HUT ke-2 Pusat Disabilitas Unhas. Tapi lebih dari itu, ia adalah bentuk nyata dari semangat kolektif untuk mengubah arah pembangunan kota. Dalam kegiatan ini, kami menelusuri area pantai, mengukur kemiringan ramp, mencatat titik-titik sulit, dan berdialog langsung dengan pengunjung dan petugas. Hasilnya membuka mata banyak orang: bahwa inklusi bukan hanya tentang “menyediakan,” tapi tentang “melibatkan.”
Kami juga menggelar seminar pariwisata inklusif yang melibatkan berbagai pihak. Di sana, kami menyatukan pengetahuan dari banyak kepala: akademisi, birokrat, pegiat difabel, dan relawan. Forum ini membuktikan bahwa inklusi tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Ia adalah hasil kolaborasi.
Puncaknya, kami mendeklarasikan Makassar sebagai Kota Pariwisata Inklusif. Di hadapan lebih dari seratus peserta, kami menandatangani komitmen bersama. Komitmen bahwa Makassar tidak boleh dibangun hanya oleh narasi, tapi oleh tindakan nyata. Dan deklarasi ini bukan penutup. Ia adalah awal dari perjuangan panjang.
Tourism For All adalah pengingat bahwa kota bukan hanya milik mereka yang kuat berjalan, tajam melihat, dan fasih berbicara. Kota adalah milik semua. Dan Makassar akan menjadi kota besar bukan karena gedung-gedung tinggi atau promosi wisata yang mewah, tapi karena keberaniannya membuka ruang bagi semua warganya untuk ikut membangun.
Sudah saatnya Makassar tidak lagi dibangun berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan partisipasi. Inklusi bukan opsi. Inklusi adalah jalan utama. Dan kami, para penyandang disabilitas, bukan hanya ingin didengar. Kami ingin ikut menentukan arah, ikut menulis sejarah.
Makassar yang inklusif bukanlah mimpi. Ia adalah kemungkinan nyata—asal kita membangunnya bersama, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.







