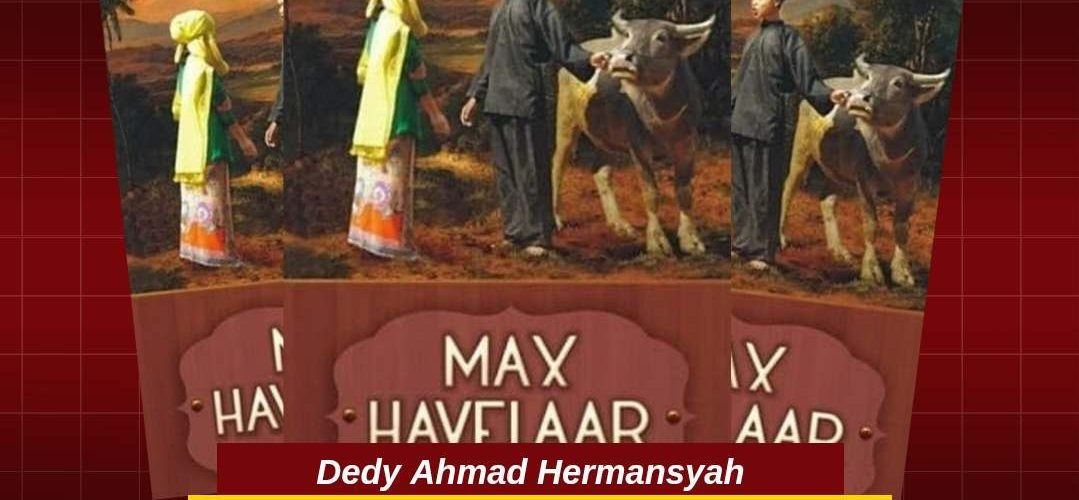Judul : Max Havelaar
Penulis : Multatuli
Penerbit : Qanita
Tahun : Cetakan XVIII, Mei 2019
Tebal : 480 halaman
Pramoedya Ananta Toer, sastrawan sohor Indonesia, pernah menjadikan novel “Max Havelaar” yang ditulis oleh Multatuli sebagai rekomendasi bacaan bagi politisi:
“Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli, bisa menjadi politikus kejam. Pertama, dia tidak mengenal sejarah Indonesia. Kedua, tidak mengenal humanisme secara modern.”
“Max Havelaar” adalah novel fenomenal yang terbit pada paruh kedua abad 19, yakni pada 1860. Ditulis oleh Multatuli—nama samaran dari Eduard Douwes Dekker—selama 18 tahun pengabdiannya sebagai Pegawai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, tepatnya di wilayah Lebak, Jawa Barat.
Novel ini memicu banyak gerakan kemanusiaan di negeri Belanda setelah penerbitannya, memaksa pemerintah kolonial Belanda memeriksa kembali kebijakan mereka di tanah jajahan yakni di Indonesia. Seluruh borok penguasa kolonial maupun lokal ditelanjangi dalam novel ini. Isu humanisme semakin ramai dibicarakan seturut dengan begitu banyaknya orang membaca buku tersebut.
Lalu mengapa harus “Max Havelaar” atau Multatuli sebagaimana disarankan Pram? Ya, pertama, karena novel otobiografis yang tragis, lucu, dan humanis ini ditulis oleh ‘orang dalam’ pemerintah kolonial Belanda, yang membongkar praktik culas nan koruptif pejabat Belanda juga sekaligus penguasa lokal yakni para raja dan bangsawan.
Kedua, novel dengan tiga narator ini mengangkat isu-isu kemanusiaan atau humanisme modern. Humanisme jenis ini berangkat dari sentimen persaudaraan sesama manusia tanpa memandang kasta dan ras, serta menolak supranatural dan bersandar pada ilmu pengetahuan.
Ketiga, novel bersetting Rangkasbitung di Banten ini juga secara reflektif mengajak kita melihat betapa kekuasaan yang korup atau pemimpin yang hanya memperkaya diri akan berakibat pada laku penindasan terhadap rakyat. Dan yang jadi kasus nyata dalam novel ini adalah sistem tanam paksa pemerintah kolonial yang dimulai pada 1830 yang berdampak pada pemiskinan dan kelaparan rakyat jelata.
Sebab itulah, tak heran jika Pramoedya Ananta Toer mengharapkan novel ini dibaca oleh politisi Indonesia agar mereka bisa mengenal bangsanya sendiri beserta sejarahnya, tidak berlaku korup dan memperkaya diri, dan senantiasa melihat sesama bangsa sendiri sebagai saudara yang tak boleh ditindas dan dibuat lapar.
“Max Havelaar” berkisah tentang penindasan pemerintah kolonial Belanda dan penguasa Pribumi kepada warga atau rakyat biasa. Kesewenang-sewenangan dipraktikkan dengan terang oleh para pejabat: mereka merampas ternak warga, sawahnya diambil paksa, atau dibeli dengan harga yang tak sesuai.
Tokoh Max yang merupakan asisten residen melihat bosnya sendiri, Residen Banten, melenggangkan penindasan itu dengan membiarkan semua kejadian itu terjadi. Lalu si bos yakni si Residen membuat laporan yang berbeda dengan kenyataan sesungguhnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Max yang tidak tahan melihat kejadian memiriskan itu terjadi di depan hidungnya lantas melaporkannya ke Gubernur Jenderal. Namun, yang terjadi malah laporan Max ditolak dan dia lantas dipecat atau diberhentikan.
Tentu dari perspektif kritis ada banyak bias dalam novel ini melihat sudut pandang cerita dari seorang pejabat kolonial sendiri, yang betapapun punya hati nurani, tentu dibatasi oleh posisinya sebagai pengabi pemerintah kolonial. Namun di luar itu semua, secara umum kita akan melihat praktik kebijakan penguasa, baik kolonial dan lokal, sering kali tidak berpihak kepada rakyat biasa.
Novel yang sering ditenteng oleh orang Eropa saat mengunjungi Indonesia ini juga jadi perhatian besar para penulis atau pegiat sastra Indonesia. Novel ini pertama kali diterjemahkan oleh HB Jassin, Paus Sastra Indonesia yang sangat berjasa dalam menjaga arsip-arsip karya sastra Indonesia dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, yang jadi referensi ulasan ini adalah versi penerbit qonita yang diterjemahkan oleh Ingrid Dwijani Nimpoeno.
Betapapun novel fenomenal ini diperdebatkan, beberapa kenyataan tak bisa dibantah: Max Havelaar membuka mata orang-orang Belanda terhadap praktik sesungguhnya pemerintah mereka di seberang lautan yakni di Indonesia. Dia mengusik humanisme liberal orang Eropa, khususnya masyarakat Belanda. Maka lahirlah program politik etis yang diniatkan jadi semacam ‘politik balas budi’, namun rupanya tetap saja melanjutkan kolonialisme dengan gaya baru.
Salah satu kutipan yang sangat menggugah dalam novel ini adalah kata-kata naratornya saat menggambarkan kegembiraan rakyat saat panen. Multatuli, lewat kutipan berikut, mengajak kita berefleksi, apa sejatinya kegembiraan rakyat biasa itu.
“Karena kita bergembira bukan kareng memotong padi; kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah, tapi bergembira untuk mendapatkan upah itu.”