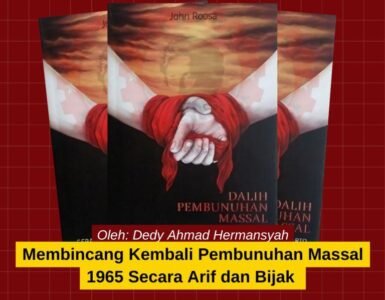Judul : Rasina
Penulis : Iksaka Banu
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun : cetakan kedua, Juni 2023
Tebal : xxiv+587 halaman
Barangkali tema sejarah masih sedikit diulik oleh para penulis fiksi kita. Namun, di antara yang sedikit itu, karya-karya fiksi Iksaka Banu menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bagi saya bukan hanya perkara membalikkan sudut pandang tokoh dari pribumi kepada mata dan batin orang Eropa. Lebih jauh dari itu: ulikan sejarah dalam fiksi-fiksinya seakan hendak menantang jiwa nasionalisme kita yang barangkali masih kekanak-kanakan, membawa kita pada refleksi apa sesungguhnya kolonialisme itu, bagaimana tidak hitam putihnya sesuatu yang bernama kebaikan dan kejahatan.
“Rasina”, karya fiksi teranyar Iksaka Banu, masih menawarkan hal-hal yang diudar di atas. Kesetiaannya pada tema sejarah—Iksaka telah menerbitkan kumpulan cerpen dan novel—khususnya sejarah Indonesia dengan ragam persoalan dan aneka zaman membuat “Rasina” menjadi novel yang renyah sekaligus bergizi, jembar sekaligus dalam—ibarat menyelam ke palung paling dalam.
Terbilang tebal, nyaris 600 halaman, Rasina justru tidak menjadi bacaan yang kehilangan fokus. Meski memadukan dua linimasa—masa-masa awal VOC dan ketika Batavia telah menjadi pusat aktivitas kolonial—namun “Rasina” dijalin dengan kualitas sang pengarang yang piawai dalam tema kolonialisme di Indonesia. Belum pula alurnya yang sesungguhnya sederhana, dengan realisme yang mudah diikuti.
Seperti disebutkan, novel ini memang mengambil dua lini masa: pertama, masa menjelang kebangkrutan VOC, tahun 1755. Masa ini dipenuhi dengan laku korup para pegawainya sendiri. Kedua, masa lebih seabad sebelumnya, tahun 1621 saat VOC tengah berupaya menaklukkan daerah Banda tempat rempah-rempah berasal. Masa pertama, tahun 1755, mengetengahkan perjuangan dua orang petugas hukum, Jan Aldemart Staalhart dan Joost Worstveld, menegakkan keadilan dengan moral khas kolonial. Masa pertama ini menjahit masa kedua—tahun 1621 yang notabene lebih seabad sebelumnya—melalui surat kakek Jan Aldemart bernama Hendrik Cornelis Adam.
Jika dirangkum secara sederhana, “Rasina” berkisah tentang jejak berdarah sejarah VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie), perusahan dagang besar milik Belanda, di Indonesia. Melalui dua linimasa tadi, kita akan melihat perkembangan perusahaan dagang besar ini dari awal kedatangannya ke Banda lalu mendirikan Batavia hingga menjelang kebangkrutannya.
Nah, di dalam sepak terjang keberadaannya inilah kita akan melihat drama yang memilukan dalam “Rasina”: jejak perbudakan dan betapa amis sejarah rempah-rempah di Nusantara. Drama itu dikisahkan oleh narator pada masing-masing linimasa—linimasa pertama dikisahkan oleh Joost Borstveld dan yang kedua oleh Hendrik Cornelis Adam—dengan detail, presisi terhadap ujaran-ujaran yang hanya ada pada saat itu (contohnya, tidak ada kata “korek api”karena belum ada kata itu pada masa tersebut, namun ‘tondeldoos’).
Karakter masing-masing tokoh tak kalah menariknya untuk diikuti, khususnya dua tokoh yang paling menonjol: Jan Aldemaar dan Joost Borstveld. Melalui dua tokoh ini kita akan mengetahui dan memahami moral dan standar kebaikan ala bangsa Eropa. Mereka datang ke Batavia selain dengan tugas professional namun juga dengan idealisme bahwa kebaikan dan keadilan harus ditegakkan.
Mari saya kutipkan sedikit panjang bagian yang menyinggung standar moral yang dimaksud:
“Orang terbiasa menggunakan kekerasan untuk membangun wibawa dan kesetiaan. Mereka lupa bahwa Raja Salomo dahulu dihormati karena kebijaksanaan dan ketegasannya. Kadang ketegasan berwujud kekerasan memang diperlukan, Salomo juga melakukannya, asalkan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Itu sebabnya lukisan Raja Salomo dipasang di lantai dua ruang sidang utama Balai Kota Batavia agar kita, para penegak hukum, meniru teladannya.”
Raja Salomo adalah sosok yang jadi panutan para penegak hukum Belanda. Jan Aldemaar nampak menjadi tokoh yang gigih sekali agar bagaimana teladan Raja Salomo dapat digunakan untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap pribumi, mereka yang menjadi budak tapi ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh tuan Eropa mereka.
“Rasina” adalah contoh pribumi yang ditindas oleh tuan Eropanya. Dia budak perempuan dari Banda yang dijadikan obyek birahi dan kekerasan oleh tuannya, Jacob de Vries. Lidahnya dikerat atau dipotong sehingga ia tak bisa bersuara. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Rasina dicekoki opium dan candu sebelum dijadikan budak seks.
Pada diri Rasina, perempuan kecil yang jelas tak berdaya di hadapan bangsa kolonial yang gagah dan angkuh, kita akan melihat semua jejak berdarah dan menyakitkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Rasina menjadi saksi mata, korban langsung kolonialisme, kasta paling rendah yang ada di Nusantara. Rasina adalah budak yang sekaligus perempuan—perpaduan maha paripurna untuk melihat penindasan.
Dan semua ironi tersebut dialirkan melalui narasi yang begitu lancar, menyerap emosi, dan penuh perumpamaan yang pas saat mendeskripsikan detail-detail penindasan kolonialisme. Mari saya kutipkan salah satunya, saat si narator hendak membandingkan luka sayatan di punggung beberapa budak dengan laku menyadap damar:
Di Nagapattinam dulu aku pernah menyaksikan penduduk setempat mengambil getah damar…mula-mula mereka melukai batang pohon dengan golok di beberapa tempat setinggi kepala manusia. Cairan bening mengucur ke luar dari luka bacokan itu dan membentuk jalur-jalur lurus yang membasahi sekujur batang… Itulah ingatan yang hinggap kembali di benakku saat mengamati bekas luka di punggung beberapa budak yang tadi diperlihatkan Tuan Staalhart.”
“Rasina” adalah novel yang akan melempar kita ke dalam palung sejarah kita sendiri, sambil berefleksi kembali tentang apa sebetulnya penjajahan itu. “Rasina” jelas bukan hanya akan menjadi bacaan yang tepat untuk para penggemar fiksi sejarah, namun juga penting dibaca oleh kalangan yang peduli pada isu-isu kemanusiaan.